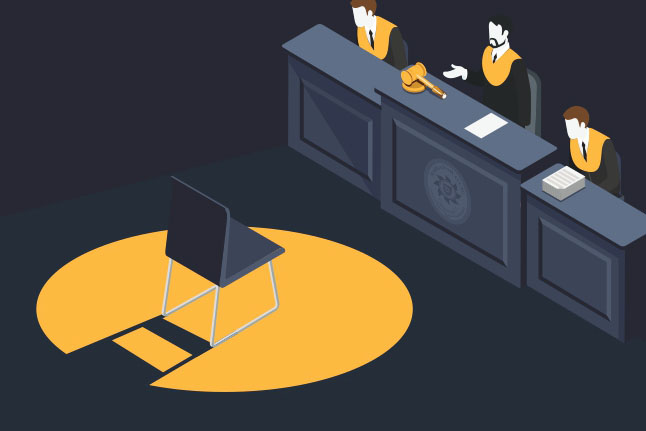Beberapa hari lalu, majelis hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Sumatera Utara, menjatuhkan vonis kepada seorang perempuan bernama Meiliana (44 tahun) selama 18 bulan penjara. Terdakwa Meiliana dinilai terbukti melakukan ujaran kebencian dan penodaan agama, karena melanggar Pasal 156a KUHP.
Hal ini bermula dari keluhan Meiliana terkait kerasnya suara adzan di lingkungan dia tinggal. Akibat keluhannya itu memicu terjadinya kerusuhan, di mana sekelompok orang membakar dan merusak Wihara dan Klenteng di Tanjung Balai. Kejadian ini terjadi pada 29 Juli 2016 silam.
Sebagaimana dikutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Medan, perkara bernomor registrasi: PDM-05/TBALAI/05/2018 itu menyebutkan, bahwa Meiliana telah ditahan sejak 30 Mei 2018 hingga sekarang. Vonis ini pun menuai kritik dari sejumlah kalangan.
Salah satunya datang dari Ketua PBNU bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan, Robikin Emhas. Menurutnya, seseorang yang mengatakan suara adzan terlalu keras tidak dapat disebut telah menista agama. "Saya tidak melihat ungkapan suara adzan terlalu keras sebagai ekspresi kebencian atau sikap permusuhan terhadap golongan atau agama tertentu," kata Robikin sebagaimana dikutip dari Antara, Selasa (21/8).
Sebagai muslim, lanjut Robikin, pendapat seperti itu sewajarnya ditempatkan sebagai kritik konstruktif dalam kehidupan masyarakat yang plural. Menurut dia, lahirnya pasal penodaan agama antara lain untuk menjaga harmoni sosial yang disebabkan karena perbedaan golongan atau perbedaan agama/keyakinan yang dianut.
"Saya berharap penegak hukum tidak menjadikan delik penodaan agama sebagai instrumen untuk memberangus hak menyatakan pendapat," kata Robikin yang juga advokat konstitusi itu.
Terpisah, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menilai hukuman yang diterima Meilina mestinya tak perlu terjadi. Pasalnya tak semua persoalan di tengah masyarakat mesti bermuara di pengadilan. Sebab persoalan yang menyangkut hubungan antar agama mestinya dapat diselesaikan melalui mekanisme musyawarah mufakat. Dengan kata lain dalam bahasa hukum disebut jalan keadilan restoratif, yakni dengan memulihkan dan mengakomodir kepentingan semua pihak.
“Masalah tersebut sebenarnya bisa diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, tidak harus dengan menggunakan pendekatan pidana. Sebab hukum pidana adalah pilihan atau opsi terakhir dan sering disebut juga dengan istilah Ultimum Remedium,” ujarnya di Komplek Gedung Parlemen.
Kendati Meiliana melakukan upaya banding misalnya, majelis hakim tinggi Sumatera Utara, lanjut Basarah, dapat memutus perkara dengan tetap menjaga kemandirian di atas kepentingan semua golongan. Cara ini dipercaya dapat menjaga persatuan dan toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Lebih lanjut Basarah yang juga menjadi anggota Komisi III DPR itu pun meminta majelis hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang menangani upaya banding Meilina dapat memperhatikan asas perlakukan yang sama dan adil di hadapan hukum. Sebab dengan perlakuan yang adil bakal mampu menjaga kepercayaan masyarakat kepada marwah lembaga peradilan.
Baca:
- MK Tegaskan UU Penodaan Agama Konstitusional
- PK Ditolak, Ini Kata Pengacara Ahok
- 2 Komika Terlilit Persoalan Hukum, Ini Kata Akademisi
RKUHP Lebih Karet
Kritikan yang sama juga datang dari Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara Suwahju. Menurutnya, pasal-pasal mengenai penistaan agama seharusnya dicabut, karena ICJR mencatat pada implementasinya, pasal-pasal tersebut menyerang dan merugikan kelompok minoritas.
“Persoalan ini terjadi karena rumusan Pasal 156a KUHP adalah rumusan yang tidak dirumuskan dengan sangat ketat dan karenanya dapat menimbulkan tafsir yang sangat beragam dalam implementasinya. ICJR mengingatkan bahwa putusan ini akan berakibat buruk bagi iklim toleransi di masyarakat serta merugikan kepentingan kelompok minoritas lainnya yang seharusnya dilindungi,” kata Anggara di Jakarta, Kamis (23/8).
Anggara menjelaskan bahwa kebebasan beragama dan kebebasan berpendapat telah dijamin oleh UUD 1945. Salah satu perlindungan beragama ditunjukkan dengan dijaminnya larangan tindakan penghasutan, permusuhan dan kekerasan yang menghasilkan diskriminasi atas dasar kebangsaan, ras atau agama dalam Pasal 20 ayat (2) ICCPR yang sudah diratifikasi oleh Indonesia.
Dalam konteks perlindungan beragama dalam hukum pidana, menurut Anggara, harus diluruskan kembali pada perbuatan materil menghasut untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan. Kerangka hukum tentang penistaan agama harus benar-benar secara ketat membatasi perbuatan yang dapat dipidana hanya dalam konteks terjadi penghasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan berdasarkan agama.
Lebih lanjut Anggara berpandangan kasus yang menjerat Meiliana merupakan satu dari sekian banyak kasus dengan penerapan Pasal 156 a KUHP. Namun praktiknya, penuntut umum maupun hakim gagal membuktikan membuktikan unsur “dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan yang pada pokoknya bersifat permusuhan”. Anggara berpandapat penerapan Pasal 156 a cenderung digunakan dalam menyerang kelompok minoritas agama tertentu.
Atas dasar itulah rumusan pasal penistaan agama mesti dirumuskan secara serius dan penuh kehati-hatian. Pasalnya berkaitan erat dengan subjektivitas mayoritas dan tendensi publik. Lantas bagaimana dengan perumusan dalam RKUHP? Menurut Anggara pengaturan tentang penistaan agama berdasarkan draf RKUHP per 9 Juli 208 diatur dalam Pasal 326, 327, 328. Ironisnya, pengaturan dalam RKUHP soal pasal penghinaan agama jauh lebih ‘karet’ dan sumir dibandingkan dengan rumusan Pasal 156 a KUHP.
“Unsur ‘dengan sengaja melakukan penghasutan untuk permusuhan’ yang menjadi safeguard dan syarat pengaturan hukum yang mengatur penistaan agama, justru dihilangkan, diganti hanya dengan unsur ‘penghinaan terhadap agama’ dengan definisi yang sangat sumir dan karet,” ujarnya.
Menurut Anggara, hukum pidana khususnya tentang penghinaan agama tidak boleh digunakan untuk melindungi suatu hal yang sifatnya subjektif, abstrak dan merupakan suatu konsep seperti negara. Kemudian simbol nasional, identitas nasional, kebudayaan, pemikiran, agama, ideologi dan doktrin politik. (ANT)