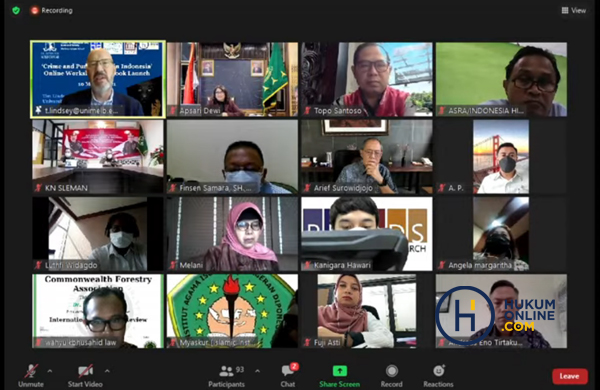Puluhan tahun praktik penegakan hukum di Indonesia masih terus menjadi sorotan dan kajian publik. Tak hanya soal penerapan pasal-pasal pemidanaan dalam KUHP dan di luar KUHP, tapi juga praktik penghukuman (hukuman pidana) terhadap orang yang dinilai terbukti bersalah oleh pengadilan. Kajian itu terangkum secara lengkap dalam buku berjudul Crime and Punishment in Indonesia.
Buku setebal 500-an halaman itu mengulas situasi kontemporer penegakan hukum di Indonesia dengan beragam permasalahannya. Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari sejumlah skolar Australia serta para pegiat hukum di Indonesia yang umumnya merupakan kandidat doktor di Universitas Melbourne Australia.
Salah satu penulis tentang praktik penghukuman pemidanaan di Indonesia, Rifqi Assegaf. Pria yang dikenal pegiat pembaharuan hukum ini mengulas kajian tentang implementasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batas Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP.
Perma 2/2012 sempat mengalami perbaikan. Semula nilai barang/benda maksimum seharga Rp200 ribu masuk kategori Tipiring. Namun angka tersebut dinilai masih rendah. Alhasil, nilai barang/benda dalam Perma 2/2012 diperbaiki atau dinaikan menjadi Rp2,5 juta menjadi angka maksimal masuk kategori Tipiring.
“Apabila terjadi pencurian nilai maksimal Rp2,5 juta seharusnya digunakan pasal tipiring ini, kecuali ada unsur pemberat tertentu,” ujar Rifqi Assegaf dalam diskusi dan peluncuran buku Crime and Punishment in Indonesia secara virtual, Rabu (10/3/2021) kemarin. (Baca Juga: Mengulas Crime and Punisment di Indonesia)
Dia menuturkan Perma 2/2012 untuk memastikan adanya keadilan bagi pelaku kejahatan ringan. Lahirnya beleid ini merespon berbagai kritik atas peristiwa pelaku pencurian beberapa buah kakau dan tipiring lainnya yang dijatuhi hukuman pidana di luar batas kewajaran, sehingga mengusik rasa keadilan. Melalui Perma 2/12, semestinya hukuman maksimal pidana selama 3 bulan penjara. Secara otomatis pelaku tidak dapat ditahan karena ancaman hukumannya kurang dari 5 tahun penjara.
Pria yang berhasil menggondol gelar doktor hukum dari University of Melbourne, Australia ini pernah melakukan penelitian terhadap 890 putusan terkait perkara pencurian dan penggelapan berdasarkan database di laman direktori putusan MA. Dari jumlah putusan itu, terdapat 45 kasus dengan 58 pelaku perkara Tipiring dan penggelapan ringan, ironisnya tak ada satupun pelaku yang dituntut dan dihukum dengan menggunakan pasal Tipiring sesuai dengan Perma 2/2012 ini.
“Rata-rata hukuman (tergolong, red) tidak rendah. Sekitar 7,6 bulan penjara. Jadi ini jauh dari pidana maksimum 3 bulan penjara yang seharusnya dijatuhi pada kejahatan Tipiring (sebagaimana amanat Perma 2/2012),” paparnya.
Misalnya, pelaku pencurian tas seharga Rp1,5 juta dan dituntut 18 bulan. Hukuman pidana yang dijatuhkan majelis hakim pun sesuai tuntutan penuntut umum, 18 bulan penjara. Ada pula pelaku pencuran ban dengan nilai kerugian Rp300 ribu. Jaksa pun menuntut 6 bulan penjara dan majelis hakim mengganjar hukuman pelaku selama 4 bulan penjara. Hukuman tersebut boleh dibilang tetap berada di atas batas maksimal hukuman kasus Tipiring.
Dia membandingkan dengan beberapa putusan di pengadilan Jakarta dan Bandung, nyaris tak terdapat perkara yang diputus dengan pasal Tipiring, seolah Perma 2/2012 tak berlaku. Sementara beberapa putusan pengadilan di Sumatera terdapat 30-40 putusan perkara pencurian kelapa sawit diputus dengan pasal Tipiring sesuai dengan Perma 2/2012. Dengan begitu, peneliti senior Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) itu menilai terdapat perbedaan praktik penghukuman antara pengadilan di Jakarta dengan kota lainnya terkait penghukuman perkara Tipiring.
Secara random, mayoritas pelaku diputus pidana percobaan. Mereka dituntut pasal tipiring dihukum percobaan. Bila jaksa menuntut dengan pasal Tipiring, hakim bakal memvonis hukuman percobaan. Temuan lain, mayoritas pelaku Tipiring diganjar hukum pidana penjara. Dan biasanya, dalam proses penyidikan pelakunya telah ditahan di kepolisian atau Kejaksaan dan sebagian besar pelaku dijerat tidak menggunakan pasal Tipiring.
“Untungnya, biasanya kasus-kasus demikian meski dihukum penjara, lamanya hukuman dekat dengan lamanya penahanan yang dilalui pelaku.”
Menariknya, ada sebagian hakim berani membebaskan terdakwa lantaran jaksa salah menuntut. Misalnya, semestinya dituntut dengan Tipiring, malah menuntut perkara tindak pidana biasa. Ada pula hakim yang berani menghukum di luar tuntutan jaksa dengan menggunakan Tipiring. Dia menilai sebuah perkara yang diproses sebelum persidangan amat berpengaruh dengan putusan majelis hakim.
“Jadi bagaimana polisi menyidik ditahan atau tidak, bagaimna jaksa menuntut dengan tipiring atau tidak, itu menentukan putusan hakim. Jadi pengaruh proses penyidikan dan penuntutan itu mempengaruhi hukuman pidana,” lanjutnya.
Rifqi melihat kondisi tersebut mendorong pola penghukuman. Bila pelaku telah ditahan di tingkat penyidikan, hakim dalam putusannya bakal mengganjar hukuman pidana penjara. Menjadi pertanyaan, alasan polisi menahan pelaku di tingkat penyidikan? Bagi Rifqi hal tersebut menjadi kultur penegakan hukum, seperti polisi memerlukan waktu menyidik
“Agar pelaku tidak melarikan diri, polisi menggunakan pasal lain. Sebab, menggunakan pasal Tipiring, polisi tak dapat melakukan penahanan. Akhirnya hakim memutus dengan pasal di luar tipiring juga,” katanya. (sampe sini).
Persoalan pidana korporasi
Sementara penulis seputar isu kejahatan korporasi di sektor lingkungan, Mas Achmad Santosa menilai pertanggungjawaban pidana korporasi penting untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) dan hak alam. Ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama, tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan korporasi berdampak serius terhadap kerugian negara, kerugian ekonomi masyarakat yang menjadi korban. Kemudian merugikan keselamatan dan kesehatan jiwa manusia, hilangnya sumber daya alam, dan ekosistem bagi ketahanan alam serta ciri khas bangsa.
“Ini penting untuk melindungi kepentingan HAM. Contoh pembakaran hutan yang berakibat pada kesehatan manusia, merugikan negara tetangga, dan berkontribusi terhadap buruknya kualitas udara,” kata Mas Ahmad Santosa.
Kedua, pencurian sumber daya ikan yang dilakukan secara masif, sistematis, dan eksploitatif. Dampaknya menipisnya pasokan ikan dan sumber ketahanan pangan yang berujung merugikan negara dalam jumlah besar. Ketiga, pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang mengancam kesehatan jiwa dan kerugian negara. Sifat dampak kejahatan lingkungan ini bersifat laten. Saat pencemaran lingkungan terjadi, dampaknya baru bisa dirasakan 10 tahun kemudian.
“Itu kenapa pertanggungjawaban pidana korporasi diperlukan di sektor lingkungan hidup,” ujar Pria yang akrab disapa Ota ini.
Menurut Ota, praktik penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia terdapat beberapa permasalahan. Pertama, belum semua peraturan perundang-undangan mengatur konsep corporate crime liability (CCL). Terlebih, KUHP belum mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi. Kedua, peraturan perundang-undangan telah mengatur tanggung jawab pidana korporasi dengan mengadopsi CCL, tapi tak seragam. Seperti UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang diubah dengan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketiga, KUHAP belum memberikan petunjuk komprehensif tentang bagaimana CCL dapat diimplementasikan.
“Meskipun terdapat Peraturan Jaksa Agung (Perja) dan Perma yang memberi petunjuk komprehensif bagi penegak hukum terhadap penerapan pasal-pasal CCL.”
Keempat, belum banyak yurisprudensi yang dapat dijadikan acuan menginterpretasikan peraturan CCL yang telah ada. “Sangat mendesak amandemen KUHP dan KUHAP mengatur jelas memadai tentang CCL dan penerapannya,” ujar anggota pembina Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) itu.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof Topo Santoso menilai buku Crime and Punishment in Indonesia sangat mendalam kajiannya. Namun, Prof Topo memiliki catatan yakni ada jenis kejahatan HAM yang dimasukkan dalam Rancangan KUHP (RKUHP). Dia menilai pembahasan RKUHP dan RKUHAP tak dapat dibahas semua dalam buku tersebut. Dia mencontohkan KUHP yang belum mengatur adanya subjek tindak pidana korporasi.
“Tapi terdapat banyak UU di luar KUHP yang mengatur pidana administratif terhadap tangggung jawab pidana korporasi,” kata Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini.
Soal hukuman atau pemidanaan, menurutnya, kajian soal ketidakakuratan sistem pemidanaan dan sistem pemasyarakatan menarik dibahas. Apalagi soal tindak pidana dengan pemidanaan minimum (tipiring) di berbagai peraturan masih mengundang persoalan over kapasitas Lapas dan Rutan di Indonesia. “Banyaknya orang memasukan pemenjaraan untuk tindak pidana yang minor seperti Tipiring. Ini saya kira sangat menarik untuk dibahas,” sarannya.