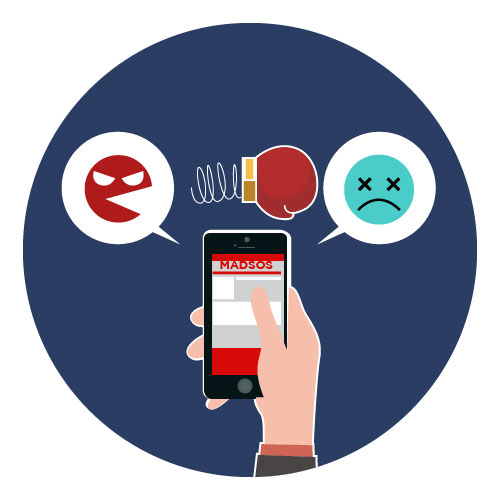“Sandiwara kebohongan” penganiayaan yang dialami aktivis Ratna Sarumpaet akhirnya diungkap sendiri melalui konperensi pers di rumahnya pada Rabu (3/10). Ratna mengaku tidak dianiaya dan membenarkan luka lebam di wajahnya karena prosedur bedah plastik. Sehari kemudian, Ratna ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Polda Metro Jaya atas laporan Ketua Umum Cyber Indonesia, beberapa komunitas advokat.
Ratna dan beberapa pihak lain dijerat Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) dan/atau Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan/atau Pasal 14 dan/atau Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) atas tuduhan menyebarkan berita bohong alias hoak yang dinilai menimbulkan keonaran di masyarakat. Lantas, apakah pasal-pasal yang disangkakan kepada Ratna Sarumpaet (RS) Dkk sudah tepat?
Direktur Eksekutif Institute Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara menilai terlepas dari persoalan politik yang melingkupi kasus ini, pasal yang disangkakan terhadap RS rentan dipersoalkan. Sebab, melihat kasus posisi yang dialami RS belum memenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan terutama unsur yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat.
“Tetapi, perbuatannya hanya menimbulkan keonaran di kalangan netizen, tidak menyebabkan matinya seseorang dan hilangnya harta benda seseorang. Sehingga, kasus ini masih jauh dari perbuatan yang dapat dipidana,” kata Anggara saat dikonfirmasi Hukumonline, (8/10/2018).
Dia membandingkan dengan kasus dugaan penyebaran berita bohong mengenai jenis vaksin bagi anak-anak yang pernah beredar di masyarakat. Pemberitaan mengenai vaksin mengandung bahan berbahaya dan juga haram menyebabkan orang tua enggan memberi vaksin terhadap anak-anaknya. Akibatnya, banyak anak yang menderita sakit akibat berita bohong ini. Namun, respon penegak hukum berbeda dengan kasus RS.
“Seharusnya kasus vaksin seperti ini yang ditindaklanjuti oleh polisi, karena berita bohong vaksin ini jaul lebih berat dampaknya,” kata dia. Baca Juga: Advokat Ini Laporkan Fadli Zon Dkk Terkait Kebohongan Ratna ke MKD
Pasal 14 KUHP Ayat (1) “Barangsiapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun.” Ayat (2) “Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun. Pasal 15 KUHP “Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.” Pasal 28 UU ITE Ayat (1) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Ayat (2) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).” |
Menurut Anggara pasal-pasal pidana penyebaran berita bohong terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi. Pertama, berita bohong harus dengan sengaja atau memiliki niat (jahat) untuk menimbulkan keonaran di kalangan rakyat. Kedua, orang tersebut harus mengetahui bahwa berita tersebut adalah berita bohong atau setidak-tidaknya harus memiliki persangkaan bahwa berita tersebut berita bohong.
Unsur pertama merupakan unsur paling krusial untuk dibuktikan yakni unsur “keonaran”. Keonaran yang dimaksudkan memiliki ukuran terjadi pergolakan dan kepanikan di masyarakat. Sementara dalam kurun waktu unggahan kesembilan orang tersebut beredar, tidak ada ‘keonaran’ atau ‘keributan’ apapun yang terjadi yang menimbulkan pergolakan di dalam masyarakat.
“Ukuran keonaran yang ditetapkan pasal ini sangat tinggi, sehingga penegak hukum tidak dapat secara serampangan menetapkan seseorang sebagai tersangka apabila unsur ini tidak terpenuhi. Hukum pidana ini tidak hanya melihat tindakan bohongnya saja, tetapi melihat dampak dari bohongnya tersebut,” kata Anggara.
Unsur kedua, orang yang menyebarkan berita bohong dan berlebihan harus mengetahui bahwa berita tersebut memang benar berita bohong atau patut menduga bahwa berita tersebut adalah berita bohong. Dalam contoh kasus ini, sebagian besar masyarakat yang menyebar berita bohong ini tidak mengetahui kebenaran yang ada di balik berita tersebut. Hal ini yang harus digali secara hati-hati oleh aparat penegak hukum. Sebab, unsur ini berhubungan dengan niat jahat pelaku tindak pidana (mens rea), apakah benar niat jahat tersebut ada di dalam perbuatannya. Jika niat jahatnya tidak dapat diketemukan dalam dirinya, maka perbuatan tersebut tidak dapat disebut sebagai tindak pidana ini.
“Bila hanya bohong masih jauh untuk dapat dipidana, kecuali berita bohong disertai keonaran dan disertai korban jiwa dan hilangnya nyawa seseorang. Saya juga tidak melihat apakah kasus RS dapat dikenai pasal lain.” (Baca Juga: Pentingnya Pembuktian Unsur Pidana dalam Menjerat Penyebar Hoaks)
Tidak dapat diterapkan
Senada, Pengajar Hukum Pidana Universitas Trisaksi, Abdul Fickar Hadjar menilai Pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak dapat diterapkan dalam kasus RS. Sebab, penyebaran berita bohong dalam media elektronik, RS tidak menyinggung SARA karena ketentuan pasal itu mensyaratkan adanya unsur kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA.
Demikian pula Pasal 35 UU ITE yang intinya adanya unsur manipulasi informasi elektronik. Padahal, RS tidak pernah menyampaikan tindakannya (kebohongan) melalui elektronik. Sekalipun kepolisian menjerat Pasal 55 dan 56 UU ITE, sangkaan pasal kedua pasal itu masih harus dibuktikan lebih jauh bahwa RS menyuruh menyebarkan. “Jadi, tidak tepat menjerat RS dengan pasal-pasal pidana dalam UU ITE,” kata Abdul Fickar kepada Hukumonline.
Menurutnya, pasal yang paling mungkin untuk menjerat RS melalui sangkaan Pasal 14 KUHP, tetapi itupun harus dapat dibuktikan korelasi tindakannya itu dengan keonaran yang timbul di kalangan rakyat. “Pengamatan saya belum ada aturan lain. Terlalu berlebihan kalau hanya berita bohong pendekatannya dipidana,” kata dia.
Selain itu, dalam pembuktian perlu ada kesadaran dan pengetahuan RS bahwa kabar yang disampaikan kepada pasangan calon presiden itu akan menimbulkan keonaran. “Namun, tidak bisa, jika tidak disadarinya berakibat keonaran, artinya tidak ada tindakan langsung RS yang sengaja ditunjukan untuk terjadinya keonaran di masyarakat,” jelasnya.
Bagi Fickar, kasus RS seharusnya tidak perlu dibawa ke ranah hukum. Sekarang ini seolah semua urusan dapat diselesaikan di kantor polisi dan berakhir dipenjara. Seharusnnya, kata dia, akibat perbuatan RS, kariernya secara politik dan etika moralnya sudah mati (habis). “Memang harusnya cukup sampai disitu saja proporsi kasus ini (tidak perlu diproses polisi, cukup matinya karier perpolitikan dan etika moral Ratna, red).”
“Tidak ada urusan ke penjara, kecuali kebohongannya nyata menyerang harkat dan martabat orang lain,” kata dia.
Harus timbul akibat
Staf Pengajar STHI Jentera, Miko Ginting, berpendapat kasus ini masuk dalam delik penyebaran berita bohong, menyesatkan, dan tidak lengkap. Tapi perlu diingat, perbuatan ini harus menimbulkan akibat terjadinya keonaran. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU No.1 Tahun 1946. “Yang menentukan terjadi keonaran atau tidak itu penuntut umum di persidangan dan diputus hakim,” ujarnya.
Miko mengkritik UU No.1 Tahun 1946 yang sangat longgar karena tidak memuat unsur kesengajaan. Akibatnya bisa berdampak buruk terhadap kebebasan berekspresi. Yang terpenting dilakukan aparat yakni menyeimbangkan upaya penegakan hukum yang dilakukan dengan kebebasan berekspresi.
Dia menilai delik yang diatur Pasal 14 dan 15 UU No.1 Tahun 1946 sifatnya materil yakni harus ada akibatnya. Polisi bisa memproses kasus ini tanpa adanya laporan dari masyarakat. “Tapi penting untuk dicatat, delik ini bermasalah karena bisa menjerat banyak kalangan termasuk jurnalis,” kata dia.
Miko juga mengkritik upaya paksa yang dilakukan kepolisian dalam menangani kasus ini. Miko mencermati sejumlah upaya paksa yang dilakukan aparat seperti penggeledahan di RS, mengambil buku register, rekaman CCTV, dan membuka rekening untuk melihat data transaksi. Menurutnya upaya paksa ini tidak dapat dilakukan dalam proses penyelidikan. “Ini peristiwa pidana belum ditemukan, tapi upaya paksa sudah dilakukan."