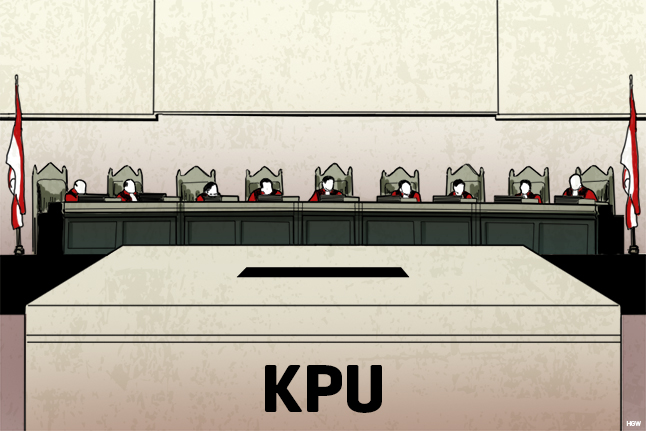Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019, baik pemilu legislatif (pileg) maupun pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres), Rabu (17/4) lalu. Namun, pelaksanaannya menyisakan sejumlah persoalan mulai dugaan pelanggaran, kesalahan prosedur administratif, hingga menelan banyak korban meninggal dunia. Dan faktanya anggaran penyelenggaraan pemilu serentak ini jauh lebih mahal ketimbang pemilu secara terpisah.
Sudah diperkirakan sebelumnya, sistem pemilu serentak yang pertama kali diterapkan di Indonesia merupakan pemilu tersulit/terumit karena menggabungkan antara pileg dan pilpres secara bersamaan. Pemilu model ini lazim disebut pemilu lima kotak (lima surat suara) sesuai UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kecuali pelaksanaan Pemilu di DKI Jakarta. Baca Juga: MK Putuskan Pemilu Serentak Tahun 2019
Membahas sistem pemilu serentak, tak bisa lepas dari putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 yang dimohonkan pakar komunikasi politik Effendi Gazali Dkk. Pada Kamis 23 Januari 2014 silam, Majelis MK yang diketuai Hamdan Zoelva membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pilpres yang mengatur pelaksanaan pilpres tiga bulan setelah pelaksanaan pileg atau tidak serentak. Namun, putusan MK yang memerintahkan pemilu serentak baru bisa diterapkan pada Pemilu 2019.
Alasan utama MK dalam putusan ini, ditinjau sudut pandang original intent, makna asli perumus perubahan UUD 1945, telah terdapat gambaran visioner mengenai mekanisme penyelenggaraan pilpres secara bersamaan dengan pileg (pemilu lima kotak/surat suara) sesuai bunyi Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 dan penafsiran sistematis Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Selain itu, pembiayaan penyelenggaraan pilpres dan pileg secara serentak akan lebih efisien dan lebih menghemat anggaran serta mengurangi gesekan horizontal masyarakat.
Lalu, DPR bersama pemerintah akhirnya mengakomodir putusan MK tentang pemilu serentak itu melalui Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017. Pasal 167 ayat (3) jo Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu menyebutkan pemungutan suara diselenggarakan secara serentak pada hari libur atau diliburkan secara nasional. Artinya, pelaksanaan pemilu serentak menggabungkan antara pilpres dan pileg secara bersamaan.
Jika ditelusuri, disain pemilu serentak sebenarnya sudah disinggung dalam Putusan MK No. 51-52-59/PUU-VI/2008. Permohonan ini diajukan Partai Bulan Bintang, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Buruh, Partai Peduli Rakyat Nasional, dan Partai Republika Nusantara. Saat itu, mereka memohon pengujian Pasal 9 UU Pilpres terkait ambang batas presiden, Pasal 3 ayat (5) terkait pelaksanan pilpres yang dilaksanakan setelah pemilu legislatif (DPR, DPD, DPRD).
Dalam Putusan MK No. 51-52-59/PUU-VI/2008 ini, MK menolak permohonan pemohon. Namun, terdapat tiga hakim konstitusi mengajukan dissenting opinion (pendapat berbeda) yakni Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, dan M. Akil Mochtar. Ketiganya berpendapat pemilu serentak dapat digelar di tingkat nasional yakni DPR, DPD dan dan Presiden serta Wakil Presiden. Sedangkan, pemilu serentak tingkat daerah untuk memilih calon anggota DPRD dan kepala daerah.
Artinya, putusan ini telah memberi definisi yang dimaksud dengan “pemilu serentak”, memisahkan antara pemilu nasional dan pemilu daerah (lokal). Namun, berbeda dengan Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 yang tidak memberi definisi yang jelas terkait sistem pemilu serentak? MK yang saat itu diketuai Hamdan Zoelva seolah menyerahkan kepada pembentuk UU untuk memberi pengertian mengenai pemilu serentak.
Kontradiksi
Mengomentari dua putusan MK itu, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran Prof Susi Dwi Harijanti menilai efek pemilu serentak pangkal persoalannya terletak pada putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 yang menghapus norma pelaksanaan pilpres tiga bulan setelah pelaksanaan pileg dalam UU Pilpres pada Januari 2014 silam. Sebab, dalam Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 ini, MK tidak memberi definisi yang jelas dan tuntas apa yang dimaksud dengan pemilu serentak. Jika dibandingkan dengan putusan MK No. 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menyatakan pilpres dan pileg digelar terpisah tetap konstitusional.
“Dalam putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 tidak menjelaskan dan memberi petunjuk dari ‘pemilu serentak’. Mahkamah justru menyerahkan kepada pembuat UU untuk menafsirkan frasa ‘serentak’ dalam UU Pemilu,” bebernya. (Baca Juga: Dilema Sistem Pemilu Serentak)
Menurut Prof Susi, MK tidak konsisten karena kedua putusan MK itu kontradiksi. Padahal aturan yang diuji sama terkait dengan aturan pemilu anggota DPR, DPR, DPR, DPRD dan presiden serta wakil presiden. Semestinya, MK dalam putusan 14/PUU-XI/2013 konsisten dengan Putusan MK 51-52-59/PUU-VI/2008. Apalagi, Prof Maria Farida saat itu memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) dengan memegang teguh putusan MK 51-52-59/PUU-VI/2008.
“Seharusnya, Putusan MK Tahun 2014 dalam pertimbangannya, dapat menggunakan dalil-dalil yang termuat dalam Putusan MK Tahun 2008,” kata Susi.
Dalam pertimbangan Putusan MK No. 51-52-59/PUU-VI/2008 terkait jadwal pemilu yang termuat dalam Pasal 3 ayat (5) berbunyi, “Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilu DPR, DPRD dan DPD.” Mahkamah berpendapat hal tersebut merupakan cara atau persoalan prosedural pelaksanaan yang tidak bertentangan dengan hukum dan konstitusi.
Pertimbangan ini sama dengan pendapat tiga hakim MK yang mengajukan dissenting opinion, yang menyatakan pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan setelah pemilu legislatif tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Tapi, dalam putusan MK No. 14/PUU-XI/2013, MK berpendapat sebaliknya, Pasal 3 ayat (5) UU Pilpres dinyatakan bertentangan dengan konstitusi (inkonstitusional). Namun, putusan MK ini berlaku pada Pemilu Tahun 2019.
Dosen Hukum Tata Negara STIH Jentera, Bivitri Susanti menilai pemilu serentak masih relevan diterapkan pada Pemilu Tahun 2024 mendatang. Menurutnya, sistem pemilu serentaknya bisa menggunakan model pemilu daerah terlebih dahulu, baru kemudian pemilu pusat.
Bivitri beda pendapat dengan Prof Susi terkait konsistensi putusan MK itu. Menurut Bivitri, Putusan MK Tahun 2014 telah konsisten dengan Putusan MK di Tahun 2008, bahkan sejak putusan MK Tahun 2005. Pendapat berbeda dalam Putusan MK Tahun 2008 tidak berarti dapat dimasukan dalam Putusan MK Tahun 2014, tetapi benar-benar pertimbangan putusan MK Tahun 2008 yang menjadi bahan pertimbangan dalam Putusan MK Tahun 2014.
Dia menerangkan jika dilihat keseluruhan dalam putusan MK Tahun 2014, MK telah menjelaskan lebih dulu putusannya di Tahun 2008 untuk memperjelas bahwa mereka sebenernya konsisten dalam memutus perkara di tahun 2008. Namun, dengan mempertimbangkan kondisi lain, MK tahun 2014 memiliki pertimbangan yang lain dan putusan yang berbeda dengan tahun 2008.
Terkait persoalan Putusan MK Tahun 2014 yang tidak memberi waktu pelaksanaan pemilu serentak yang seperti apa dan hanya menyerahkan semuanya kepada kebijakan pemerintah, menurut Bivitri hal ini MK juga tidak salah. Sebab, MK hanya menjawab constitutional question yang hanya menjelaskan pasal tersebut konstitusional atau tidak. Untuk hal-hal teknis lain sejak tahun 2005 yakni Putusan MK No. 010/PUU-III/2005, hal ini merupakan open legal policy yang harus ditentukan oleh pembentuk UU.
Perlu diperhatikan pula, kata Bivitri, aspek teknis manajemen pelaksanaan oleh KPU dalam menyelenggarakan pemilu itu sendiri agar tidak lagi terjadi dampak yang mengakibatkan korban jiwa. “Putusan MK terkait pemilu serentak bukan satu-satunya penyebab terjadinya banyak memakan jatuh korban, tetapi manajemen pelaksanaan pemilu oleh KPU yang perlu dievaluasi lebih baik lagi,” kata Bivitri kepada Hukumonline, Rabu (15/5/2019).
“Dalam rekrutmen petugas pemilu diperlukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu untuk menjadi petugas dalam pemilu mendatang. Hal ini untuk mengantisipasi kelelahan yang dapat memicu kematian,” katanya. (Baca Juga: Pemilu Serentak, Haruskah 'Dirombak' Total?)
Bukan yang diinginkan
Pakar Komunikasi Politik Effendi Gazali, salah satu pemohon Putusan MK No, 14/PUU-XI/2013, mengatakan Pemilu Serentak 2019, bukan pemilu serentak yang dia inginkan. Sebelum Pemilu 2019 terlaksana, Effendi telah meminta MK untuk membatalkan pemilu serentak setelah mengetahui hasil UU Pemilu di DPR tanggal 21 Juli 2017 yang kemudian menjadi UU No. 7 Tahun 2017 terutama masuknya aturan presidential threshold.
Menurut Effendi, pemilu serentak seharusnya tanpa presidential threshold. Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva pernah bercerita kepada dirinya pada 2017 lalu bahwa sebetulnya saat para hakim MK memutuskan pemilu serentak, mereka sepakat tidak ada presidential threshold. Lalu, Effendi bertanya, “Kenapa tidak dituliskan saja bahwa tidak ada presidensial threshold dalam putusan MK tentang pemilu serentak?” Hamdan menjawab “kami pikir tidak akan ada logikanya memasukkan presidential threshold dalam pemilu serentak.”
“Jadi, disitulah masalahnya, tidak ditulis oleh MK. Kalau ditulis oleh MK, maka tidak akan ‘terbelah’ bangsa kita seperti ini,” kata Effendi Gazali kepada Hukumonline.
Bagi Effendi, pemilu serentak harus memiliki dua tujuan. Pertama, melaksanakan dengan konsisten original intent Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 bahwa pemilu harus serentak. Sebab, perlu diingat Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tidak pernah diubah. “Pemilu serentak tanpa presidential threshold karena para pendiri bangsa dan pembentuk UUD 1945 ingin seluruh putra putri terbaik bangsa banyak yang bisa maju sebagai capres dan cawapres.”
Meski begitu, Effendi berpendapat pemilu serentak tetap bisa dijalankan yakni Pemilu Nasional Serentak dan Pemilu Daerah Serentak tanpa presidential threshold untuk menjalankan original intent pendiri negara dan pembentuk UUD 1945. “Ke depan, seharusnya MK dapat mendefinisikan arti keserentakan apa itu, belajar dari evaluasi Pemilu Serentak 2019. Sebab, kita menganut asas the living constitution, misalnya MK membenarkan interpretasi pemilu nasional serentak dan pemilu daerah serentak,” ujarnya.
Bahkan, lanjutnya, ada juga yang berpendapat keserentakan dalam pemilu itu adalah pencalonan atau pendaftaran calon ke KPU yang serentak, jadi bersamaan antara capres dan caleg. Tetapi pelaksanaannya bisa tetap dipisah. “Yang penting oligarki dan politik transaksional dipotong dan tidak ada presidential threshold,” pintanya.
Dia juga menyoroti manajemen Pemilu Serentak 2019 yang dinilianya kewalahan. ia menyarankan agar ke depan KPU harus menyiapkan manajemen pemilu yang tertib dengan melibatkan semua ahli. Ia pun mengusulkan pemungutan suara dapat dilakukan dengan e-voting. “Ini DPR sudah studi banding kemana-mana kok tidak ketemu e-voting yang murah dan bisa dipercaya,” kata dia.
Seperti di USA, ia mencontohkan voting tetap pakai surat suara yang dicoblos, tapi langsung tersimpan dalam mesin dan langsung bisa di-scan dan dibaca, hasil pemilihanya pun bisa di-print dan disimpan oleh pemilih. “Dan, tidak perlu mencontoh Jerman yang semua kertas suara ada dalam mesin, sehingga dapat menyebabkan kehilangan dalam big data.”
Karena itu, Prof Susi menyarankan beragam persoalan yang muncul dalam penyelengaraan pemilu serentak perlu dievaluasi secara “radikal”. Dimulai dengan menghapus/meniadakan aturan ambang batas pencalonan presiden. Ketika ketiadaan electoral atau ambang batas, maka perlu dilakukan simulasi terlepas apakah sistem pemilunya serentak atau tidak. Namun, bila pemilu tetap digelar secara serentak, MK mesti memberi petunjuk kepada pembuat UU. (Baca Juga:Problematika Pemilu Serentak, Perlu Evaluasi ‘Radikal)
Saat ini beberapa warga negara telah mendaftarkan uji materi kata “serentak” dalam Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimohonkan oleh beberapa lembaga pemantau pemilu pada 10 Mei 2019, lalu. Adanya uji materi terkait pemilu serentak ini, Bivitri mempersilakan bagi warga negara yang ingin menguji ke MK.
“Dalam uji materi tentang pemilu serentak nanti, ada pembahasan bersama secara terbuka terkait Pemilu Serentak 2019 dengan perdebatan-perdebatan ilmiah sekaligus menjadi tempat evaluasi bersama,” kata Bivitri.