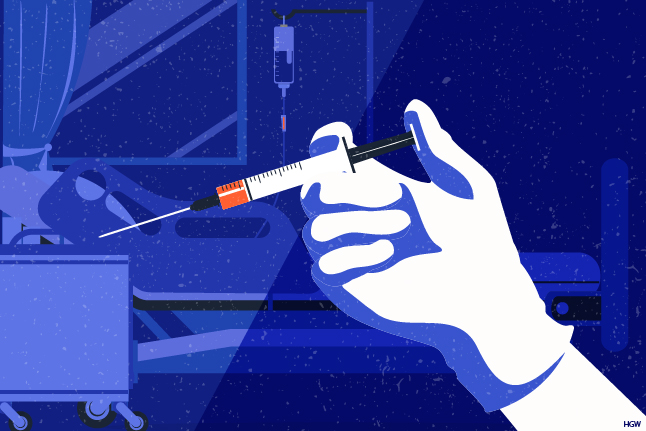Euthanasia telah lama menjadi bahan perdebatan kalangan medis, hukum, aktivis hak asasi manusia, dan agamawan. Terlepas dari perdebatan itu, orang yang mengajukan euthanasia terus bertambah, terutama di negara-negara yang melegalkan ‘mati dengan cara baik’ itu. Yang terakhir adalah euthanasia atas permintaan atlit paralimpik Belgia, Marieke Vervoort. Suntikan dokter mengakhiri hidup perempuan 40 tahun itu pada Oktober lalu.
Belgia salah satu negara yang mengakui dan melegalkan euthanasia. Pengakuan hukum terhadap euthanasia malah sudah lebih dahulu di Belanda. Namun sebagian besar negara tak mengakui dan membenarkan tindakan euthanasia. Indonesia termasuk yang tak mengakui hak untuk mengakhiri hidup semacam itu. Ahli hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie, berpendapat jika hak untuk mati diakui seperti halnya hak untuk hidup, risikonya besar. Sama saja memberikan legalisasi pada orang yang ingin melakukan bom bunuh diri dengan alasan pengakuan right to die.
Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), M. Choirul Anam, mengatakan euthanasia juga menjadi perdebatan di dunia internasional. Dalam perkembangannya, ada yang mengarah pada legalisasi dengan catatan penting. Pertama, euthanasia dibenarkan karena cukup alasan yang sangat kuat, misalnya kesehatan yang memburuk dan sulit disembuhkan. Kedua, pengakhiran hidup pasien dilakukan oleh orang yang profesional dan bertanggung jawab. Ketiga, dilakukan melalui prosedur yang ketat. “Itu masih menjadi perdebatan,” ujarnya kepada hukumonline.
Begitulah faktanya, sudah banyak literatur di Indonesia yang menulis tentang euthanasia, sebagian besar memuat doktrin dan kode etik kedokteran, serta akibat hukumnya. Sekadar memberi contoh, Kuitert dan F Tengker menerbitkan hampir dua puluh tahun lalu buku ‘Kematian yang Digandrungi: Eutanasia dan Hak Menentukan Nasib Sendiri’. Sebelumnya sudah ada tulisan Djoko Prakoso dan Djaman Andi Nirwanto, “Euthanasia: Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana”.
Jejak perdebatan kontemporer tentang euthanasia di Indonesia selalu merujuk pada dua kisah. Pertama, kisah Hasan Kusuma. Pada 22 Oktober 2004, Hasan Kusuma mengajukan permohonan izin ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar isterinya, Again Isna Nauli, diberi tindakan euthanasia. Sang isteri sudah tergolek dalam keadaan koma selama dua bulan, plus kesulitan yang dialami untuk membayar perawatan medis. Tersiar kabar pada saat itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak permohonan euthanasia tersebut.
(Baca juga: Terbentur Masalah Administratif, Penetapan Euthanasia Ny Again Tertunda).
Kisah kedua merujuk pada Ignatius Ryan Tumiwa. Lulusan pascasarjana dari salah satu universitas terkemuka ini ingin mengakhiri hidupnya dengan cara suntik mati. Tetapi permohonannya terhalang Pasal 344 KUH Pidana, yang mengancam dokter atau tenaga medis lain yang membantu seorang pasien mengakhiri hidup. Melalui pengacaranya, Ryan mengajukan permohonan pengujian pasal itu ke Mahkamah Konstitusi. Pada Agustus 2014 lalu, permohonannya dicabut. Alasannya, Ryan sudah punya semangat untuk menjalani kehidupan lagi. Pencabutan permohonan itu disambut positif hakim konstitusi yang memeriksa permohonan ini.
Ditolak pengadilan
Sebenarnya, ada satu kisah yang lebih lengkap dibanding kasus Nyonya Again dan Ryan. Permohonan euthanasia yang diajukan Berlin Silalahi (BS) malah sudah diputuskan pengadilan. Berdasarkan penelusuran hukumonline, permohonan euthanasia diajukan Berlin ke Pengadilan Negeri Banda Aceh pada Mei 2017 lalu. Pemohon adalah korban tsunami Aceh yang terjadi pada 24 Desember 2004. Seperti sejumlah korban lain, BS ditempatkan di barak Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Selama dua tahun di sana, BS menunggu bantuan perumahan yang layak.
Rumah yang ditunggu belum terealisasi, BS dipindahkan ke barak lain di Gampong Tibang, kecamatan Syiah Kuala. Di sini, BS bersama isteri dan anak bungsunya tinggal selama 2,5 tahun. Ia kembali dipindahkan ke barak lain di Bakoy Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Di barak inilah BS tinggal sejak 2009 hingga mengajukan permohonan euthanasia.
Permohonan euthanasia diajukan lantaran sakit yang diderita BS sejak 2013. Pria kelahiran 1971 itu sudah lumpuh dan tak dapat lagi mencari nafkah untuk keluarganya. Kebutuhan sehari-hari banyak dibantu penghuni barak. Selain lumpuh, BS menderita sakit kronis, infeksi peradangan pada tulang, dan asma sehingga tidak dapat melakukan aktivitas apapun. Pengobatan medis ke rumah sakit dan pengobatan tradisional sudah dijalani namun tak kunjung sembuh. Penderitaan pemohon semakin berat karena kepala daerah memerintahkan bongkar paksa barak yang ditinggali pemohon. Itu sebabnya, BS mengajukan permohonan euthanasia ke pengadilan. Surat pernyataan dari BS, surat persetujuan isteri, dan surat konsultasi dari dokter spesialis sudah dilampirkan sebagai bukti.
Ternyata, permohonan BS ditolak pengadilan. Hanya dalam waktu dua pecan, hakim tunggal sudah mencapai kata sepakat untuk ‘menolak permohonan pemohon’. Hakim merujuk pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kode Etik Kedokteran, dan Pasal 344 KUH Pidana. Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan punya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sesuai amanat Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam kaitan itu, hakim tak hanya melihat peraturan perundang-undangan, tetapi juga hukum Islam yang dianut pemohon, dan hukum adat setempat.
Hakim Ngatemin yang memutus permohonan ini mengutip pandangan Majelis Ulama Indonesia bahwa euthanasia dilarang karena keputusasaan, dan tidak diperkenankan dalam Islam. Kemudian hakim mengutip sejumlah ayat Al Qur’an dan Hadits yang pada intinya melarang membunuh diri sendiri. “Menimbang bahwa sesuai dengan agama yang dianut oleh Pemohon, yaitu agama Islam, bahwa berputus asa dalam hukum Islam tidak dibenarkan, begitu halnya terhadap sebuah penyakit yang sedang diderita oleh seseorang, sehingga euthanasia tidak seharusnya dilakukan demi mengakhiri penderitaan,” demikian antara lain pertimbangan hakim.
Dalam hukum adat pun, kematian dianggap sebagai takdir Tuhan. Euthanasia dengan cara disuntik dapat dianggap sebagai bunuh diri. Bunuh diri adalah perbuatan yang dilarang baik dalam adat maupun agama. Dari sisi hukum positif pun, ada larangan melakukan euthanasia, meskipun hakim mengakui belum ada aturan yang secara khusus mengatur euthanasia. Karena itu, hakim berketatapan hati untuk menolak permohonan BS.
Sentil Pemerintah
Dalam pertimbangannya, hakim sempat ‘menyentil’ pemerintah. “Bila melihat dan membaca permohonan pemohon pada intinya pemohon mengharapkan peran pemerintah dalam hal ini pemerintah Aceh terhadap masyarakat yang kurang mampu”. Dilanjutkan sang hakim dalam pertimbangan: “jadi, dari kasus ini dihubungkan dengan UU Pemerintahan Aceh, diharapkan peran pemerintah lebih baik lagi”.
Setelah itu, hakim menyimpulkan bahwa euthanasia merupakan tindakan yang keliru untuk dilakukan seseorang meskipun dengan alasan untuk mengakhiri penderitaan. Sebab, penderitaan masih dapat diatasi dengan upaya lain tanpa harus melakukan suntik mati atau cara euthanasia lainnya. UU Hak Asasi Manusia, tegas majelis, tak mengatur hak untuk mati. Jadi, euthanasia merupakan suatu tindakan yang bertentangan dan melanggar UU Hak Asasi Manusia.
Penasehat hukum BS dari Yayasan Advokat Rakyat Aceh, Safaruddin, menjelaskan kliennya tak mengajukan banding atas putusan itu. Setelah permohonan euthanasia diajukan petugas Dinas Sosial sudah datang dan memberikan bantuan kepada kliennya. “Diberikan tempat yang layak,” jelas Safaruddin kepada hukumonline, Rabu (20/11).