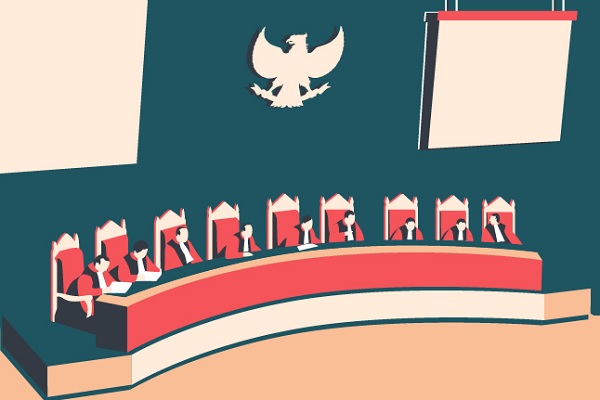Solusi terkait pernikahan beda agama hanya dapat dilakukan dengan konversi agama. Untuk itu, pernikahan dapat dilakukan sesuai agama yang sudah disatukan dalam keyakinan yang sama yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Pandangan itu disampaikan Hairunas selaku Ahli yang dihadirkan pemerintah dalam sidang lanjutan pengujian Pasal 2 ayat (1), (2) dan Pasal 8 huruf f UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait syarat sahnya perkawinan dan larangan menikah oleh agamanya.
Permohonan ini diajukan E. Ramos Petege, yang memeluk agama Khatolik, pernah hendak menikah dengan seorang wanita yang memeluk agama Islam. Tetapi, setelah menjalin hubungan selama 4 tahun dan hendak menikah, perkawinan tersebut harus dibatalkan karena kedua belah pihak memiliki agama dan keyakinan yang berbeda.
Hairunas menyampaikan dampak dari pernikahan beda agama ditinjau dari perspektif psikologis. Keyakinan agama merupakan hak individu sebagai warga negara, yang hakikatnya tidak dapat dipaksakan oleh seseorang kepada yang lainnya termasuk mengubah keyakinannya. Menurutnya, pemaksaan pindah agama karena hubungan pernikahan sebenarnya dapat melukai psikologis seseorang yang cenderung emosional sesaat.
Dia juga melihat pernikahan beda agama dapat menciderai dan mengganggu kestabilan kerukunan keluarga kedua pihak baik calon istri maupun calon suami. Lebih konkrit berdasar sisi psikoterapi dan kesehatan mental, pelaku pernikahan beda agama cenderung sulit berinteraksi dalam keluarga. Terlebih, jika keduanya memiliki anak karena akan mendapati pilihan berat dan dilematis untuk mengikuti salah satu agama yang dianut orang tuanya.
Baca Juga:
- MUI Minta MK Tolak Perkawinan Beda Agama
- Pandangan DPR-Pemerintah Terkait Perkawinan Beda Agama
- Inlah Babak Akhir Judicial Review Kawin Beda Agama
“Dari sisi agama manapun, secara teologis, ritualistis, dan normatif memiliki perbedaan terpaut jauh. Karenanya perilaku beragama diantara pasangan berbeda keyakinan dapat menimbulkan sengketa hati dan pikiran, sehingga rentan pada perpecahan dan keresahan mendalam kedua belah pihak,” ujar Hairunas yang merupakan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam persidangan, Kamis (11/8/2022) seperti dikutip laman MK.
Hairunas berpendapat cinta hanyalah emosi sesaat yang mungkin saja dapat mengalahkan hal yang prinsip. Untuk itu, cinta dapat pula berubah karena hal yang prinsip, seperti sakralitas dari agama itu sendiri. Karenanya, pasangan beda agama seringkali mengalami bentrok psikologis. Apabila pasangan tersebut memiliki keturunan, anak cenderung dilematis dalam menentukan keyakinannya. Bahkan hal ini akan dirasakan berkepanjangan dan merugikan kepribadian dari salah satu diantara keduanya. Terjadinya gesekan psikologis ini dapat saja berdampak pada perceraian.
“Solusi konversi agama atau pindah agama agar dapat legal standing ini sesungguhnya belum solutif. Persoalan terkait pemilihan agama karena sebab emosi, perlu kesadaran, keikhlasan, dan hanya bisa diukur oleh personal yang akan menikah. Jika ada keinginan di balik itu, konversi agama akan menimbulkan persoalan baru,” terang Hairunas.
Ahli pemerintah lain, Euis Nurlaelawati memberi pandangan mengenai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 40 (C) yang mengatur seorang laki-laki tidak boleh melakukan pernikahan dengan seorang wanita dalam beberapa kondisi, termasuk kondisi perempuan tidak beragama Islam. Dalam hal ini kesamaan agama merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam kafaah (kesejajaran/keserasian).
“Indonesia merupakan negara dengan kategori muslim dan melarang perkawinan beda agama,” kata Euis yang merupakan Guru Besar UIN Sunan Kalijaga ini.
Dia mengakui meski banyak yang memahami UU Perkawinan tidak menetapkan hukum yang tegas terkait perkawinan beda agama ini, namun keberadaan KHI tidak memberi ruang hal tersebut dan mengakomodir fatwa MUI. Pemahaman di kalangan mayoritas para ulama, kata Euis, menyatakan perkawinan merupakan ibadah atau mengandung unsur ibadah, sehingga perkawinan beda agama dapat dikatakan tidak membawa kemaslahatan dan justru sebaliknya (mudarat).
“Kemudaratan (dampak merugikan, red) dari perkawinan beda agama ini justru dianggap masih lebih besar, sehingga menghindari atau menutupnya dipandang menjadi pilihan utama sesuai kaidah fiqih yang berbunyi dar’u al-mafâsid muqaddamun ‘alâ jalb al-mashâlih,” kata Euis.
Sebagai informasi, MK sendiri sudah pernah mengambil sikap tegas terkait polemik kawin beda agama ini melalui Putusan MK No.68/PUU-XII/2014 yang dibacakan pada 18 Juni 2015 silam. MK pernah menolak pengujian Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur syarat sahnya perkawinan terkait kawin beda agama yang dimohonkan seorang mahasiswa dan beberapa alumnus FH UI.
Kala itu, para pemohon mempersoalkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan mengenai syarat sahnya perkawinan, terutama berkaitan dengan keabsahan kawin beda agama. Norma pasal itu dinilai pemohon berimplikasi tidak sahnya perkawinan di luar hukum agama, sehingga mengandung unsur “pemaksaan” warga negara mematuhi agama dan kepercayaannya di bidang perkawinan.
Pemohon beralasan beberapa kasus kawin beda agama menimbulkan ekses penyelundupan hukum. Alhasil, pasangan kawin beda agama kerap menyiasati berbagai cara agar perkawinan mereka sah di mata hukum, misalnya perkawinan di luar negeri, secara adat, atau pindah agama sesaat. Karenanya, para pemohon meminta MK membuat tafsir yang mengarah pada pengakuan negara terhadap kawin beda agama. Namun, MK menganggap Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan sama sekali tidak bertentangan dengan UUD 1945.
Mahkamah menganggap UU Perkawinan ini telah dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD Tahun 1945 serta dapat menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Terlebih, Pasal 28J UUD 1945 menyebutkan dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap warga negara wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan Undang-Undang yang salah satunya dengan pertimbangan nilai-nilai agama.
“Karena itu, segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan warga negara termasuk dalam hal yang menyangkut urusan perkawinan harus taat dan tunduk serta tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan,” demikian bunyi salah satu pertimbangan Mahkamah.